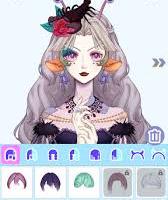Kalian pernah nggak sih suka sama sahabat kalian? Yah kali ini aku sadar kalau aku suka sama sahabat dari kecil ku. Dari umur 3 tahun hingga sekarang aku umur 23 tahun baru sadar kalau aku suka bahkan cinta sama dia. Namun bagaimana mungkin aku menyatakan perasaan ini? Kami itu sahabatan. Bagaimana aku menaruh hati dengannya/ bahkan dia juga sudah punya pacar. Pacar yang selalu dia bangga-banggakan. Aku bingung bagaimana harus mengungkapkannya!
Hai namaku Dion! Umur ku saat ini 23 tahun, aku baru saja lulus kuliah. Aku suka banget dengan kedisiplinan namun aku mendapatkan sahabat yang selalu lalai terhadap waktu dan bahkan tugasnya. Bagaimana cerita kami? Lest go
Karya ini diterbitkan atas izin NovelToon Ayinos SIANIPAR, isi konten hanyalah pandangan pribadi pembuatnya, tidak mewakili NovelToon sendiri
Voni menunggu sedari tadi
Setelah sesi belajar selesai, aku memutuskan untuk pulang. Sebelum keluar dari apartemen Reta, aku berpamitan dengan sopan. Ia mengantarku sampai ke depan pintu dengan senyum hangat yang sedikit membuatku merasa aneh, entah kenapa. Ada kenyamanan baru yang terasa sejak tadi.
Aku memesan ojek daring karena tak ingin berjalan kaki malam-malam sambil membawa amplop cokelat berisi uang yang cukup besar. Meski jarak antara rumahku dan apartemen Reta hanya sekitar lima ratus meter, aku tak mau mengambil risiko. Lingkungan ini memang aman, tapi siapa pun bisa nekat saat melihat peluang.
Selama menunggu ojek datang, aku naik lagi ke rooftop apartemen untuk menghirup udara malam. Tempat itu benar-benar nyaman. Angin malam bertiup lembut, menerpa wajahku seperti pelukan yang menenangkan. Sejak siang tadi aku sudah merasa tempat ini punya atmosfer yang berbeda. Rasanya damai, seperti tak ada beban yang berat.
Aku tersenyum sendiri. Sepertinya aku akan betah dengan pekerjaan ini. Kapan lagi jadi mentor siswa tapi digaji dua digit? Tapi, yah, hal seperti ini biasa terjadi di sekolahku. Hampir semua siswanya anak orang kaya. Mereka biasa mengeluarkan uang puluhan juta hanya untuk les privat atau keperluan akademik lainnya. Yang penting hasilnya memuaskan orang tua.
Tak lama, ojekku datang. Aku pun naik dan menuju rumah.
Sekitar lima belas menit kemudian, aku sampai di rumah. Langsung kubuka pagar pelan-pelan agar tidak membangunkan siapa pun. Aku masuk dan berjalan cepat ke kamarku, berusaha menghindari Mpok Rita, asisten rumah tangga kami yang sangat cerewet kalau tahu aku pulang selarut ini. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul sepuluh malam.
Sesampainya di kamar, hal pertama yang kulakukan adalah mandi. Air dingin menyentuh kulitku dan membuat tubuhku segar kembali. Setelah mandi, aku meminum jus beri seperti biasanya. Kalau tidak, Mama pasti curiga. Mama sangat perhatian, dan salah satu caranya menunjukkan kasih sayangnya adalah dengan mengawasi apa saja yang aku konsumsi setiap hari. Jika ia tahu aku melewatkan minum jus beri, siap-siap saja ditanyai macam-macam—dari kegiatan hari ini, pertemuan dengan siapa saja, bahkan sampai ke apa saja yang aku makan.
Setelah itu, aku berniat main gitar sebentar, hanya sekitar tiga puluh menit, untuk mengistirahatkan pikiranku. Aku melangkah ke pojok kamar, mengambil gitar akustikku yang sudah lama menemaniku melewati malam-malam sunyi. Baru saja aku memainkan intro dari lagu favoritku, tiba-tiba sebuah bantal melayang ke arahku dan tepat menghantam kepalaku.
“Plak!”
Kepalaku terdorong sedikit ke kanan karena benturan empuk itu. Aku segera menoleh ke arah asal bantal itu datang. Mataku langsung membulat saat melihat siapa pelakunya.
“Voni? Kamu kok bisa ada di sini?” tanyaku dengan wajah bingung sekaligus kaget.
Gadis berambut sebahu itu malah tertawa dan menirukan ucapanku dengan gaya mengejek. “Vonnn... kamu kok bisa ada di siniii...” katanya dengan suara dibuat-buat.
Aku mendesah, kesal setengah mati. “Aku serius, Von!”
Dia meringis geli lalu menjawab, “Aku dari jam tiga sore udah di sini. Mpok Rita bilang kamu baru keluar pas aku datang. Karena bosan nunggu dan kamu nggak balik-balik, ya udah, aku tidur di sini. Dan ternyata kamu baru datang jam segini! Dari mana aja, sih?” tanyanya dengan nada cerewet yang sangat khas dirinya.
Aku yang masih memegang gitar dan mencoba menenangkan emosi hanya menjawab singkat, “Tadi aku belajar di luar, bikin metode baru...”
Dia menatapku penuh kecurigaan. “Ih, alah! Kamu bohong! Pasti kamu pacaran, ya? Nggak usah bohong, Dion. Bau parfum cewek nempel banget di baju kamu yang ini,” katanya sambil melemparkan bajuku ke arahku.
Aku terdiam sejenak. Astaga. Setelah kucium bajuku, benar saja—bau parfum Reta sangat terasa. Mungkin ini karena tadi sore Reta sempat bersandar di pundakku saat emosinya sedang tak stabil. Aku hanya menggeleng, malas menjelaskan lebih jauh.
“Terserah kamu, deh,” ujarku kesal. Aku tahu percuma menjelaskan hal seperti ini ke Voni kalau dia sudah mulai berkhayal.
Dia tiba-tiba mengubah topik, wajahnya terlihat agak serius. “Dion, kamu ngerasa nggak sih kalau belakangan ini kita makin jauh? Sejak aku pacaran sama Varo, kamu jadi jarang ngobrol sama aku... kamu kayak menjauh.”
Aku menatapnya, kali ini benar-benar memperhatikannya. Dari cara dia bicara, matanya yang sedikit sayu, dan cara duduknya yang tidak biasa. Aku berjalan mendekatinya dan duduk di atas tempat tidurku, tepat di sebelahnya.
“Von, kamu yang menjauh, bukan aku. Aku masih kayak biasanya. Aku masih sering ke perpustakaan, masih belajar di rumah. Bahkan hari ini aku coba metode belajar baru,” jawabku pelan, mencoba membuatnya mengerti.
Dia mengangguk perlahan, seperti mencerna ucapanku. Lalu tiba-tiba dia menatapku dalam-dalam dan berkata, “Dion... kamu jangan pernah berubah ke aku, ya. Kamu bakal tetap perhatian sama aku, kan?”
Pertanyaan itu membuat hatiku menghangat. Meski sering menyebalkan dan cerewet, Voni adalah teman masa kecilku. Sudah seperti saudara sendiri.
“Iya, Voni. Kamu itu tetap aku prioritaskan setelah keluarga aku,” jawabku sambil tersenyum. Ia juga tersenyum, manis sekali.
“Siapa, sih, pacar kamu? Kamu belum mau ngenalin ke aku, ya?” tanyanya tiba-tiba dengan nada menggoda.
Aku memutar bola mataku, frustasi. “Aku nggak pacaran, Voni!”
“Iya deh, percaya,” sahutnya sambil tertawa. Dasar menyebalkan.
Karena kesal, aku mengusap rambutnya kasar, lalu mengacak-acak dengan semangat. Tak puas di situ, aku mencubit hidung mancungnya sampai memerah.
“Ih! Sakit tahu!” protesnya sambil memukul lenganku. Aku tertawa puas.
“Aku tidur di sini, ya,” ucapnya kemudian sambil merebahkan tubuhnya di tempat tidurku.
Aku mengangguk pelan. Sudah biasa. Bahkan Mama sudah menganggap dia sebagai anak perempuan sendiri. Rumah kami memang bertetangga. Mama bahkan menyiapkan seragam sekolah cadangan buat Voni di rumah ini, karena ia memang sering menginap tanpa aba-aba.
Malam itu kami menghabiskan waktu dengan bernyanyi dan bermain gitar bersama. Suara Voni sangat merdu, berbeda sekali dari kesan “pemalas” yang biasa ia tampilkan. Kalau dia mau, sebenarnya dia punya potensi besar di bidang musik. Aku tahu itu.
Saat lagu ketiga selesai, kami saling pandang dan tertawa kecil.
“Dion, makasih ya,” katanya tiba-tiba.
“Buat apa?”
“Buat tetap jadi kamu yang selalu ada,” jawabnya singkat.
Aku tak membalas, hanya tersenyum. Dalam hati, aku tahu malam itu adalah malam yang menguatkan kami lagi. Meski hidup terus berjalan, dan meski arah kami perlahan berubah, selalu ada satu momen kecil yang menjaga kami tetap dekat.
Dan malam ini… adalah salah satunya.