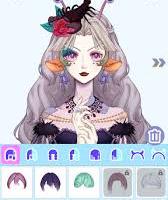Kalian pernah nggak sih suka sama sahabat kalian? Yah kali ini aku sadar kalau aku suka sama sahabat dari kecil ku. Dari umur 3 tahun hingga sekarang aku umur 23 tahun baru sadar kalau aku suka bahkan cinta sama dia. Namun bagaimana mungkin aku menyatakan perasaan ini? Kami itu sahabatan. Bagaimana aku menaruh hati dengannya/ bahkan dia juga sudah punya pacar. Pacar yang selalu dia bangga-banggakan. Aku bingung bagaimana harus mengungkapkannya!
Hai namaku Dion! Umur ku saat ini 23 tahun, aku baru saja lulus kuliah. Aku suka banget dengan kedisiplinan namun aku mendapatkan sahabat yang selalu lalai terhadap waktu dan bahkan tugasnya. Bagaimana cerita kami? Lest go
Karya ini diterbitkan atas izin NovelToon Ayinos SIANIPAR, isi konten hanyalah pandangan pribadi pembuatnya, tidak mewakili NovelToon sendiri
UJIAN TERAKHIR UJIAN KIMIA
Hari Terakhir Ujian
Hari ini adalah hari terakhir ujian, dan entah mengapa perasaanku begitu lega. Mungkin karena tekanan yang menumpuk sejak beberapa minggu lalu akhirnya bisa lepas satu per satu. Aku berangkat dari rumah bersama Voni, seperti biasanya. Namun, ya, Voni lagi-lagi lalai terhadap waktu. Gadis satu itu memang terkenal sebagai pemalas sejati—bangun pagi saja sudah jadi perjuangan besar untuknya.
“Von, ayo dong cepat! Kamu kenapa sih nggak pernah bisa menghargai waktu?” sergahku, kesal. Aku sudah berdiri di depan rumahnya sejak sepuluh menit yang lalu.
Sementara itu, Voni yang sedang mengenakan sepatu dengan terburu-buru hanya mendengus sebal. “Kamu yang terlalu cepat, Ion! Ini masih jam 06.30, masih ada waktu empat puluh lima menit, tahu!” ujarnya sambil tetap berusaha memasang tali sepatu secepat mungkin.
Aku mengabaikan protesnya. Dengan sengaja, kutarik gas motor hitamku berkali-kali, menghasilkan suara bising sebagai isyarat bahwa aku benar-benar tidak sabar. Tak lama, akhirnya Voni keluar dan naik ke motorku dengan langkah tergesa.
“Nyebelin banget sih kamu,” gerutunya sambil mengeratkan pelukannya di pinggangku. Tangannya melingkar erat, seperti biasa ketika kami berboncengan. Tapi kali ini berbeda. Ada perasaan lain yang muncul di dalam dadaku.
Selama perjalanan, Voni hanya diam. Aku bisa merasakan pelukannya erat, namun hawa tubuhnya terasa dingin. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Andai saja dia tahu betapa aku menyayanginya. Bahkan, aku rela melakukan apa pun demi melihat senyumnya. Senyum Voni itu, seolah mampu menghapus segala ketakutan dalam hidupku. Tapi aku juga bingung, apakah ini cinta atau hanya bentuk kepedulian mendalam sebagai sahabat?
Tanpa sadar, tangan kiriku menggenggam kedua tangannya yang melingkar di perutku. Genggaman itu seperti isyarat agar dia memelukku lebih erat. Aku tancapkan gas sedikit lebih dalam, mengalihkan pikiranku dari perasaan yang mulai tak karuan.
Tak butuh waktu lama, kami tiba di sekolah. Seperti biasa, beberapa siswa langsung menghampiriku—menanyakan nomor WhatsApp, meminta follow Instagram, dan segala hal yang jujur saja membuatku risih. Aku tidak terlalu suka menjadi pusat perhatian.
Tanpa pikir panjang, kutarik tangan Voni dan mempercepat langkah. Voni sampai harus setengah berlari untuk menyesuaikan langkahku.
“Cepat, Von,” ucapku pelan sambil menoleh ke arahnya. Dia hanya cemberut.
Gadis pendek ini memang selalu membuatku ingin tersenyum. Kadang ingin sekali kugendong saja, supaya dia tak perlu susah payah mengejar langkahku. Tapi aku tak pernah melakukannya. Aku masih menghargai Varo—pacar Voni saat ini. Atau… setidaknya, itu yang kupikirkan sampai tadi malam.
Setibanya di kelas, kami duduk di bangku kami seperti biasa. Sudah beberapa bulan ini kami duduk sebangku. Aku membuka buku catatan untuk mengulas kembali materi sebelum ujian dimulai. Namun, seperti biasanya, Voni tak bisa diam. Gadis pemalas itu kembali menggangguku dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak penting—tapi tetap saja aku menikmatinya.
“Ion, cewek idaman kamu itu sebenarnya kayak gimana, sih?” tanyanya tiba-tiba.
Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. “Kamu masih mikir kalau kemarin itu aku pacaran?” tanyaku, menatap matanya serius.
“Bukan gitu,” jawabnya cepat. “Kalaupun kamu nggak pacaran, berarti kamu belum pernah pacaran, kan? Makanya aku penasaran, tipe kamu kayak gimana? Atau… kalaupun kamu pacaran semalam itu, kamu belum pernah ngenalin ceweknya ke aku. Tapi dari parfumnya sih... kayaknya dia berkelas banget,” lanjutnya dengan nada menyelidik.
Aku tersenyum kecil dan menggeleng. Pola pikir Voni memang tak pernah berubah—selalu nyeleneh tapi jujur.
“Kalau kamu sendiri, yakin tipe kamu itu kayak Varo?” tanyaku balik, mencoba menggali lebih jauh.
Wajah Voni langsung berubah. Ia mendengus pelan dan terlihat seperti menahan sesuatu.
“Aku udah putus sama Varo tadi malam,” katanya pelan.
Aku terkejut. Tapi di sisi lain, aku juga merasa... senang? Entahlah, aku tak bisa menolak perasaan itu.
“Kok bisa? Kamu yang minta putus atau dia?” tanyaku lembut, menatap wajahnya yang tiba-tiba kehilangan semangat.
Dia menunduk. “Aku yang mutusin. Aku ngerasa... aku dan dia nggak saling cinta. Dia cuma manfaatin aku, dan aku juga sadar... bukan dia yang aku cari selama ini.”
Aku menatapnya iba. “Hei, it’s okay. Mungkin Tuhan belum kasih waktu yang tepat buat kamu pacaran. Kamu itu masih kecil,” ujarku, mencoba mencairkan suasana dengan nada menggoda.
Tapi Voni tetap menunduk. Wajahnya tenggelam di antara lengannya yang terlipat di atas meja. Aku menghela napas lalu mulai memainkan rambutnya yang halus. Kebiasaan lama yang biasa kulakukan saat dia sedang sedih.
Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Aku kembali berbicara, kali ini lebih lembut, “Kamu sesayang itu ya sama dia, sampai segalau ini?”
Voni mengangkat wajahnya perlahan. Matanya sedikit memerah. Ia menatapku, dan tanpa ragu berkata, “Nggak, Ion. Justru aku lebih takut kehilangan kamu.”
Kata-katanya membuatku terdiam. Rasanya seperti ada sesuatu yang meledak di dalam dadaku. Tanpa sadar, ia menggenggam tanganku—erat sekali, seakan tak ingin kulepas.
“Nggak kok... Aku janji, aku akan selalu memprioritaskan kamu seperti keluargaku,” jawabku, meyakinkan. Aku menggenggam balik tangannya, menyalurkan kehangatan dan ketulusan yang tak bisa diucapkan lewat kata-kata.
Kami diam beberapa saat. Hanya saling menggenggam tangan di atas bangku kayu yang dingin itu. Namun momen itu seperti melambat. Rasanya waktu berhenti sejenak, memberikan ruang untuk perasaan yang selama ini tersembunyi.
Namun, momen itu tak bertahan lama. Pintu kelas terbuka, dan Varo masuk. Tatapannya langsung mengarah padaku—dan Voni. Ia melihat tangan kami yang masih saling menggenggam. Tatapannya dingin, menusuk, dan tak bisa disalahartikan. Aku melepaskan genggaman tanganku perlahan, tapi tidak dengan Voni. Ia masih menunduk, wajahnya kini tampak bersalah. Aku bisa merasakan tubuhnya sedikit gemetar.
Entahlah apa yang terjadi antara mereka semalam. Tapi satu hal yang pasti: hubungan mereka benar-benar sudah berakhir.
Aku berharap Voni mau menceritakannya nanti. Aku tidak ingin memaksanya. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa lagi menyangkal perasaanku sendiri. Mungkin sudah saatnya aku jujur. Mungkin... sudah waktunya untuk tidak hanya menjadi sahabat.