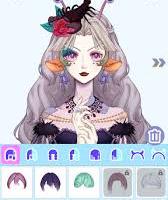Kalian pernah nggak sih suka sama sahabat kalian? Yah kali ini aku sadar kalau aku suka sama sahabat dari kecil ku. Dari umur 3 tahun hingga sekarang aku umur 23 tahun baru sadar kalau aku suka bahkan cinta sama dia. Namun bagaimana mungkin aku menyatakan perasaan ini? Kami itu sahabatan. Bagaimana aku menaruh hati dengannya/ bahkan dia juga sudah punya pacar. Pacar yang selalu dia bangga-banggakan. Aku bingung bagaimana harus mengungkapkannya!
Hai namaku Dion! Umur ku saat ini 23 tahun, aku baru saja lulus kuliah. Aku suka banget dengan kedisiplinan namun aku mendapatkan sahabat yang selalu lalai terhadap waktu dan bahkan tugasnya. Bagaimana cerita kami? Lest go
Karya ini diterbitkan atas izin NovelToon Ayinos SIANIPAR, isi konten hanyalah pandangan pribadi pembuatnya, tidak mewakili NovelToon sendiri
SE FREKUENSI MUNGKIN
Kini aku sedang berdiri di depan sebuah gedung yang menjulang tinggi. Gedung itu adalah apartemen tempat tinggal gadis aneh yang kini berjalan di sampingku. Aku menatap bangunan itu dengan bingung, bertanya-tanya dalam hati: Ngapain aku dibawa ke sini? Mau ngapain juga?
Sesekali aku melirik gadis itu. Sungguh, dalam pikiranku sempat terlintas hal-hal aneh. Dia nggak mungkin ngajak aku masuk dan... tidur bareng, kan? Nggak mungkin! Gila aja! Ya kali Dion, lu cowok, lu bisa jaga diri. Kalau dia macam-macam, gue bisa hadapi.
Pikiran itu segera kutepis. Aku menarik napas panjang saat gadis itu menatapku, lalu tersenyum.
“Kamu mau ikut aku ke lantai paling atas?” tanyanya ringan.
Aku hanya mengangguk pelan. Entah kenapa aku menurut saja.
Kami menaiki lift menuju rooftop gedung itu. Dari atas, pemandangan kota terlihat menakjubkan. Angin sore menyapa lembut wajah kami. Gadis itu mengajakku duduk di pinggiran tembok pengaman yang cukup lebar dan aman. Kemudian, ia menyodorkan tangannya ke arahku.
“Aku Reta. Aku orang yang tadi minta kamu jadi mentorku. Juga yang ganggu kamu di perpustakaan,” katanya pelan, sedikit malu dan menunduk.
“Hmm… soal itu, aku minta maaf,” ucapku canggung. Aku sendiri heran kenapa sejak tadi bisa begitu menurut dan bahkan merasa bersalah.
“Enggak. Aku yang harus minta maaf. Aku tahu tiba-tiba banget minta kamu jadi mentor. Tapi tenang aja, aku nggak akan maksa. Aku cuma pengin kamu temani aku di sini. Boleh, ya?” katanya sambil menatap langit yang masih terlihat terang keemasan.
Aku mengangguk. Entah kenapa, hatiku terasa lembut. “Boleh. Santai aja.”
“Kalau kamu juga lagi ada masalah, kamu boleh cerita ke aku. Anggap aja hari ini kita saling berbagi cerita,” ujarku tulus. Aneh juga rasanya. Biasanya aku jarang mau terbuka ke orang, apalagi yang baru kukenal. Tapi hari ini… vibes-nya beda. Sesuatu dalam dirinya membuatku merasa ingin mendengar.
Reta tersenyum. Senyum yang sederhana, tapi mengandung sesuatu. Seperti rasa lega, atau mungkin… harapan.
“Mamaku dokter,” ucapnya tiba-tiba. “Dan dia pengin banget aku ngikutin jejak dia. Tapi nilai biologi, fisika, dan kimia aku itu rendah terus. Jadi dia selalu anggap aku bodoh. Nggak berguna. Bahkan sering nyumpahin aku mati aja.”
Aku diam. Kata-katanya menyentakku. Aku menatapnya dalam-dalam. Tapi yang kutemukan bukan kemarahan, melainkan wajah pasrah. Seperti sudah terlalu sering mendengar kata-kata itu. Seperti sudah muak.
“Jadi itu alasan kamu minta aku jadi mentor?” tanyaku, penasaran.
Ia mengangguk kecil. “Iya. Jujur aja, Dion. Aku udah lama kagum sama kamu. Kamu pintar, ganteng, terkenal. Semua orang suka kamu. Cuma… wajah kamu nggak bersahabat ke semua perempuan, kecuali Voni.”
Aku terkesiap. Mendengar semua itu membuatku canggung. Tapi juga bangga. Dan, sedikit malu.
“Eh… makasih ya udah jujur. Dan muji juga,” jawabku setengah salting. Reta hanya tertawa kecil, lalu menatapku dengan mata yang mulai berkabut.
“Kalau soal ayahmu gimana, Ret?” tanyaku.
“Papi udah lama banget nggak pulang. Dan mungkin itu juga yang bikin Mama makin marah. Dia jadi ngelampiasin semuanya ke aku.”
Wajahnya kini berubah. Matanya memerah, dan bibirnya bergetar. Aku bisa melihat dia sedang berusaha menahan tangis.
“Kamu benci orang tua kamu?” tanyaku, makin penasaran. Ini mungkin pertama kalinya aku tertarik benar-benar memahami masalah orang lain selain Voni.
Reta menggeleng lemah. “Nggak akan pernah bisa. Mama tetap orang yang melahirkan aku. Papi tetap yang pernah fasilitasi hidupku. Aku cuma sedih… aku nggak bisa bahagiakan mereka.”
Tiba-tiba rasa iba muncul dari dalam dadaku. Tanpa sadar, aku mengelus kepalanya perlahan.
“Kamu bisa cerita apa aja ke aku, Ret. Kalau kamu mau nangis juga, di sini ada pundakku,” ucapku tulus.
Ia menatapku sesaat, lalu tanpa bicara langsung bersandar dan menangis di punggungku. Aku diam. Menunggu. Memberinya waktu untuk melepas beban yang selama ini ia pendam sendiri.
Air matanya membasahi bagian belakang bajuku. Tapi aku tak peduli. Mungkin, menangis adalah satu-satunya bentuk kejujuran yang bisa kita berikan pada diri sendiri saat dunia tak lagi mendengar.
Setelah beberapa menit, Reta mengusap air matanya. Ia menarik napas panjang, lalu tertawa kecil.
“Maaf ya, Dion. Baju kamu jadi basah. Maaf juga udah nyusahin,” ucapnya. “Sekarang giliran kamu. Kamu tadi bilang lagi ada masalah juga, kan?”
Aku mengangguk, mencoba menata napas. Aku tak mau menangis, apalagi di depan orang lain.
“Orang tuaku baru saja kena penipuan bisnis. Semua lahan investasi Mama habis. Sekarang, uang jajan aku dikurangi drastis.”
“Oh...” gumam Reta, menatapku prihatin.
“Sebenarnya, buat aku uang jajan nggak terlalu penting. Aku juga bukan tipe yang hura-hura. Uang tabungan juga cukup. Tapi aku khawatir sama Mama. Dia kerja siang malam buat keluarga. Dan sekarang semua lenyap begitu saja. Aku takut dia drop.”
Reta terdiam sejenak, seolah mencerna kata-kataku. Ia kemudian mengangguk pelan. “Aku ngerti banget perasaan itu, Dion. Rasanya kayak... kita pengin bantu, tapi nggak tahu gimana. Dan makin nggak enak karena mereka tetap berusaha tegar.”
Aku menatap langit. Kini senja benar-benar hampir hilang. Langit berubah menjadi biru tua dengan bintik bintang kecil yang mulai terlihat.
Angin malam mulai terasa dingin. Tapi ada sesuatu yang hangat di hatiku. Mungkin karena aku tak merasa sendirian. Mungkin karena untuk pertama kalinya aku bisa berbagi, bukan hanya menerima.
Kami duduk lama di sana. Tak banyak bicara. Hanya memandangi langit dan lampu-lampu kota yang mulai menyala.
“Ret…” kataku pelan.
“Iya?”
“Gue baru sadar… lo nggak aneh. Mungkin selama ini gue aja yang nggak pernah benar-benar mau lihat orang lebih dalam.”
Dia tertawa kecil. “Nggak apa-apa. Gue juga sadar gue sering aneh. Tapi hari ini gue senang.”
“Gue juga,” balasku. “Kayaknya... kita sefrekuensi, ya?”
Dia hanya mengangguk, tersenyum. Dan malam pun jadi saksi dua orang yang tadinya asing kini mulai merasa saling mengerti.