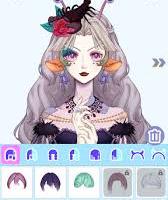Kalian pernah nggak sih suka sama sahabat kalian? Yah kali ini aku sadar kalau aku suka sama sahabat dari kecil ku. Dari umur 3 tahun hingga sekarang aku umur 23 tahun baru sadar kalau aku suka bahkan cinta sama dia. Namun bagaimana mungkin aku menyatakan perasaan ini? Kami itu sahabatan. Bagaimana aku menaruh hati dengannya/ bahkan dia juga sudah punya pacar. Pacar yang selalu dia bangga-banggakan. Aku bingung bagaimana harus mengungkapkannya!
Hai namaku Dion! Umur ku saat ini 23 tahun, aku baru saja lulus kuliah. Aku suka banget dengan kedisiplinan namun aku mendapatkan sahabat yang selalu lalai terhadap waktu dan bahkan tugasnya. Bagaimana cerita kami? Lest go
Karya ini diterbitkan atas izin NovelToon Ayinos SIANIPAR, isi konten hanyalah pandangan pribadi pembuatnya, tidak mewakili NovelToon sendiri
KETEMU DIA LAGI??
Seperti biasanya, sepulang sekolah aku akan mengganti bajuku, lalu memainkan gitar sebentar untuk melepas penat. Nada-nada kecil yang kugoreskan di senar gitar selalu berhasil menurunkan tensi setelah seharian berkutat dengan pelajaran dan tugas. Setelah itu, barulah aku belajar, biasanya hingga menjelang malam. Rutinitas itu sudah menjadi kebiasaanku sejak duduk di bangku SMP, dan kini masih kulakukan dengan disiplin.
Namun, hari ini terasa berbeda. Begitu aku membuka pintu rumah, Mpok Rita langsung menghampiriku dengan wajah serius, tak seperti biasanya yang ramah dan ceria.
“Den Dion, sini tasnya Mpok bawain, ya. Ini jus beri-nya, Den. Tadi Nyonya nyuruh Mpok kasih ini ke Den begitu sampai rumah. Setelah itu, Den disuruh langsung ketemu sama Nyonya di ruang kerja,” ucap Mpok Rita sambil menyodorkan segelas jus beri—minuman favoritku sejak kecil.
Aku menerimanya sambil mengerutkan dahi. Aneh. Mama menyuruhku menemuinya di hari Rabu? Biasanya, aku hanya bertemu Mama secara intens di akhir pekan, tepatnya hari Sabtu. Itulah waktu keluarga kami berkumpul. Kami biasanya makan malam bersama, menonton film, atau sekadar duduk bersantai di taman belakang sambil menikmati waktu. Tapi kali ini... hari Rabu, hari yang sangat sibuk bagi Mama, dan dia memintaku datang menemuinya secara khusus?
Tanpa pikir panjang, aku segera naik ke kamar, mengganti seragam sekolah dengan pakaian santai, lalu menuruni tangga menuju ruang kerja Mama. Di sana, Mama sudah menungguku di sofa berlapis beludru biru tua. Penampilannya tetap anggun seperti biasa, dengan rambut panjang yang disanggul rapi dan pakaian kerja berwarna krem yang elegan. Namun, raut wajahnya tampak berbeda. Ada kelelahan yang sulit disembunyikan, dan sorot matanya terlihat kosong.
Aku menghampirinya perlahan, mencium kedua pipinya. “Mama manggil Dion? Ada apa, Ma?” tanyaku pelan.
Mama menatapku, matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tanganku erat. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya berkata, “Akhirnya kamu datang juga, sayang.”
Aku hanya diam, menunggu kelanjutannya. Suasana jadi sangat hening.
“Mama langsung to the point aja, ya,” lanjutnya sembari menarik napas panjang. “Mama… mama kena tipu, Dion.”
Ucapannya membuat jantungku berdegup lebih kencang. Tapi aku tetap diam, menunggu dengan penuh waspada.
“Semua lahan investasi Mama di luar kota habis. Kita sekarang cuma punya satu hektare lahan sawit di kampung. Dan karena ini, mungkin Mama harus potong uang jajan kamu. Dari yang biasanya sepuluh juta per bulan, Mama cuma bisa kasih lima persennya. Mama minta maaf, Nak. Mama benar-benar bingung harus bagaimana lagi...”
Tangisnya pecah. Tangis yang tak bisa ditahan oleh gengsi, status, atau kekuatan yang selama ini selalu ia tunjukkan di depan semua orang. Dan aku, hanya bisa duduk diam mematung, bukan karena marah, tapi karena hatiku ikut hancur melihatnya seperti ini.
Aku mendekat, memeluk tubuhnya yang terasa lebih kurus. Kuusap lembut rambut panjangnya yang kini mulai dipenuhi uban.
“Tenang aja, Ma. Bahkan kalau Mama cuma bisa kasih satu persen pun, aku nggak masalah. Mama nggak usah ngasih jajan juga aku tetap oke. Yang penting Mama sehat,” kataku sambil menahan air mata.
Mama membalas pelukanku. Tangannya yang kasar karena kerja keras membelai wajahku dengan lembut. “Kamu tanggung jawab Mama, Dion. Tapi Mama gagal... Mama gagal jadi orang tua yang baik.”
Aku menggeleng perlahan, menatap matanya dalam-dalam. “Mama salah. Mama justru ibu terbaik dalam hidupku. Mama selalu kerja keras, selalu peduli. Gagal itu bukan ketika kita kehilangan segalanya, tapi saat kita menyerah. Dan Mama belum menyerah, kan?”
Mama hanya tersenyum di antara air matanya. Senyum yang menggambarkan kelegaan kecil di tengah badai yang belum usai.
Setelah pelukan itu, Mama berpamitan untuk kembali bekerja. Ia bilang akan mencoba mencari pekerjaan tambahan, apa pun itu. Aku mengangguk memahami. Aku tahu, Mama tidak akan pernah tinggal diam ketika keluarga dalam keadaan terpuruk.
Aku sendiri merasa perlu menjernihkan kepala. Maka, seperti kebiasaan lamaku, aku memutuskan untuk berjalan-jalan sore di sekitar kompleks. Langit mulai berwarna jingga, udara lembut mengelus wajah, dan aroma pohon kamboja dari pekarangan rumah tetangga terasa akrab.
Langkahku terhenti ketika aku melihat seorang ibu sedang memarahi anaknya di halaman rumah. Suaranya begitu keras hingga terdengar dari jauh. Rasa penasaran membuatku mendekat, diam-diam bersembunyi di balik pagar kecil.
“Dasar anak sialan! Mati aja kamu! Nilai aja nggak bisa bagus, apalagi hidup kamu nanti!” bentak ibu itu dengan suara parau.
Aku tercekat. Itu bukan kemarahan biasa. Itu... kekejaman. Gadis remaja keluar dari rumah dengan lutut berlutut di tanah, menangis sesenggukan. “Aku akan belajar lebih giat, Mah… ampun, Mah...”
Aku terdiam. Itu gadis yang tadi siang kutemui di perpustakaan. Gadis aneh yang dengan percaya diri memintaku jadi mentornya. Aku masih ingat wajahnya yang sedikit kaku, namun berani. Dan sekarang... dia berada dalam kondisi seperti ini?
Aku merasa sangat bersalah. Tadi aku mempermalukannya. Menolak mentah-mentah permintaannya, bahkan bersikap dingin seolah dia tak berarti. Padahal mungkin, belajar adalah satu-satunya cara baginya untuk keluar dari neraka yang ia sebut rumah.
Gadis itu akhirnya keluar dari rumah. Wajahnya sembab, langkahnya berat. Ia tampak seperti orang yang kehilangan arah. Aku, tanpa sadar, mulai mengikutinya dari belakang. Tak tahu mau berkata apa, hanya mengikuti naluriku.
Namun, di tengah jalan, dia berhenti. Tanpa menoleh, dia berkata, “Jangan mengikuti dari belakang. Sini, jalan di sebelahku.”
Aku tersentak, malu karena kepergok. “Hkm… maaf sebelumnya. Sudah lancang,” ujarku pelan.
Dia hanya mengangguk pelan. “Santai aja. Aku nggak marah, kok,” katanya lembut.
Lalu, ia menoleh dengan mata yang masih menyisakan jejak air mata. “Kamu mau ikut aku ke suatu tempat?” tanyanya tiba-tiba.
Aku bingung, tak tahu harus menjawab apa. Jantungku berdetak cepat.
“Tempatnya… aku jamin kamu bakal suka,” lanjutnya dengan suara yakin.
Tanpa sadar, aku mengangguk. Entah kenapa, aku percaya padanya.
Kami pun berjalan berdampingan, meninggalkan kompleks, menuju tempat yang belum kuketahui. Langkahku terasa ringan. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku merasa... mungkin semuanya akan baik-baik saja.